
Makassar, 21-22 Juli 2025. Pagi itu, setelah sarapan sekitar pukul 08.00 WITA, kami dijemput oleh Bang Saddan untuk melanjutkan agenda penting berikutnya: mengunjungi Museum Balla Lompoa yang terletak di daerah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Perjalanan dari tengah Kota Makassar hanya memakan waktu sekitar lima belas menit. Meski singkat, antusiasme kami terasa penuh, sebab Gowa dikenal sebagai salah satu pusat sejarah penting dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan.
Sesampainya di depan museum, kami berhenti sejenak untuk mengambil gambar. Museum Balla Lompoa sendiri dikenal sebagai rekonstruksi istana Kerajaan Gowa, sebuah simbol yang sarat sejarah. Memasuki area museum, kami disambut dengan ramah oleh kurator, Pak Jufri. Beliau dengan penuh semangat menceritakan perjalanan panjang Kerajaan Gowa: mulai dari asal-usul berdirinya, perkembangan politik dan sosialnya, hingga proses islamisasi yang menjadikan kerajaan ini salah satu pusat penting penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara.

Dalam penjelasan itu, kami kemudian ditunjukkan pada salah satu koleksi berharga museum: mushaf kuno yang tersimpan di Balla Lompoa. Kondisinya memang sudah banyak mengalami kerusakan, namun sebagian teks masih dapat dibaca. Dari data yang tersedia, mushaf tersebut merupakan karya Syekh Ahmad Umar, seorang ulama yang turut memberi warna dalam sejarah intelektual Islam Sulawesi Selatan. Ciri khas mushaf ini terlihat dari adanya parateks dan pias yang memperkaya teks utama. Setelah berbincang lebih jauh dengan Pak Jufri mengenai konteks penyimpanan dan kondisi mushaf, kami pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya: Museum La Galigo.
Sekitar pukul 11.30 WITA, kami tiba di Museum La Galigo yang berlokasi di Jl. Ujung Pandang No. 2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Museum ini merupakan salah satu pusat arsip sejarah terbesar di Sulawesi Selatan. Kami diterima dengan sangat baik oleh Kepala Museum, Bapak Ergiawan Edy. Sambil menunggu proses administrasi berupa surat disposisi, kami berbincang dengan beliau mengenai koleksi mushaf yang ada, juga tentang dinamika pelestarian naskah kuno dalam konteks museum modern.
Tidak lama kemudian, kami didampingi oleh kurator museum, Pak Ardi, yang dengan penuh keramahan mengajak kami melihat langsung koleksi mushaf yang tersimpan. Terdapat tiga mushaf yang menjadi koleksi utama di museum ini. Meskipun tidak ditemukan parateks seperti mushaf di Balla Lompoa, mushaf-mushaf ini tetap menarik karena di dalamnya terdapat kode-kode hukum tajwid yang berfungsi sebagai penuntun bagi para pembaca. Digitalisasi mushaf dilakukan dengan hati-hati, dibantu oleh Pak Ardi serta mahasiswa Program Studi Pariwisata Universitas Hasanuddin yang tengah magang di museum. Proses ini selesai sekitar pukul 17.15 WITA.

Sebelum meninggalkan museum, kami diajak masuk ke sebuah ruangan yang membuat bulu kuduk berdiri: bekas penjara Pangeran Diponegoro. Ruangan pengap dengan suasana sunyi itu menyimpan aura sejarah yang kuat. Di sanalah, tokoh besar perlawanan terhadap kolonial Belanda pernah diasingkan. Momen singkat itu menghadirkan rasa haru sekaligus refleksi, bahwa perjuangan, ilmu, dan spiritualitas kerap bertemu dalam ruang-ruang yang penuh makna sejarah.
Menjelang magrib, kami kembali dijemput Bang Saddan. Dalam perjalanan pulang, kami sempat singgah di sebuah rumah makan yang terkenal dengan sajian es pisang ijo khas Makassar. Selepas santap malam bersama Pak H. Fadly, perjalanan berlanjut ke kediaman Pak Ilham. Di sana, kami kembali disuguhi sebuah khazanah intelektual: tafsir Jalalain yang disalin oleh Syekh Zainal Abidin, ulama Bugis yang karya-karyanya memberi kontribusi besar dalam literatur Islam lokal. Proses digitalisasi tafsir ini berlangsung hingga sekitar pukul 22.00 WITA sebelum akhirnya kami kembali ke penginapan untuk beristirahat.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bang Saddan kembali menjemput kami. Setelah sarapan, kami menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Di sana, setelah berpamitan, kami melakukan check-in dan boarding. Tepat pukul 09.00 WITA pesawat lepas landas menuju Surabaya. Perjalanan udara singkat ini berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Dari Surabaya, perjalanan kembali ke Jombang, Tulungagung, dan Blitar dilanjutkan dengan moda transportasi darat berupa bus.
Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada penutupnya. Namun yang kami bawa pulang bukan sekadar hasil digitalisasi mushaf dan tafsir, melainkan juga pengalaman intelektual dan spiritual yang mengakar. Dari Gowa, Makassar, hingga ke berbagai titik lain di Sulawesi Selatan, kami melihat dengan jelas bagaimana warisan ulama Nusantara masih hidup dalam bentuk mushaf dan naskah. Tugas kita hari ini bukan hanya mendokumentasikannya, tetapi juga menjaga agar cahaya ilmu itu tetap bisa diakses oleh generasi mendatang.
Perjalanan kami selama beberapa hari di Sulawesi Selatan, mulai dari Pompanua, Bone, Wajo, hingga Gowa dan Makassar, sejatinya bukan sekadar kegiatan akademik untuk mendigitalisasi mushaf dan naskah. Lebih dari itu, ia adalah sebuah ziarah intelektual dan spiritual. Setiap museum, perpustakaan, dan kediaman ulama yang kami datangi selalu menghadirkan kesan bahwa tradisi keilmuan Islam Nusantara begitu kaya, mendalam, dan terus hidup di tengah masyarakat.
Kami menyadari bahwa mushaf-mushaf yang tersimpan, meski beberapa dalam kondisi rapuh, adalah saksi bisu perjalanan panjang umat Islam di kawasan timur Nusantara. Di balik tinta yang mulai memudar, tersimpan kisah tentang ulama, santri, dan masyarakat yang berjuang menjaga Kalamullah di tengah dinamika zaman, dari masa kerajaan hingga kolonialisme. Digitalisasi yang kami lakukan bukan hanya kerja teknis, melainkan juga bagian dari ikhtiar melanjutkan estafet penjagaan ilmu.
Namun refleksi ini juga membawa kesadaran bahwa pelestarian naskah tidak cukup berhenti pada digitalisasi semata. Ia harus berlanjut pada pengembangan riset, penyusunan narasi akademik, hingga pendidikan publik agar warisan ulama dapat dikenali, diapresiasi, dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Tugas itu tidak ringan, tetapi perjalanan ini meyakinkan kami bahwa menjaga ilmu adalah bagian dari menjaga peradaban.
Pada akhirnya, perjalanan ini meneguhkan pandangan bahwa riset manuskrip tidak hanya menyangkut teks, tetapi juga konteks: ruang, waktu, dan manusia yang melingkupinya. Dari Pompanua hingga La Galigo, dari mushaf hingga tafsir, kami belajar bahwa tradisi Islam Nusantara adalah sebuah mosaik yang harus terus dirawat dengan kesungguhan, agar cahaya pengetahuan dan spiritualitas yang dititipkan para ulama tidak padam di tengah arus zaman.
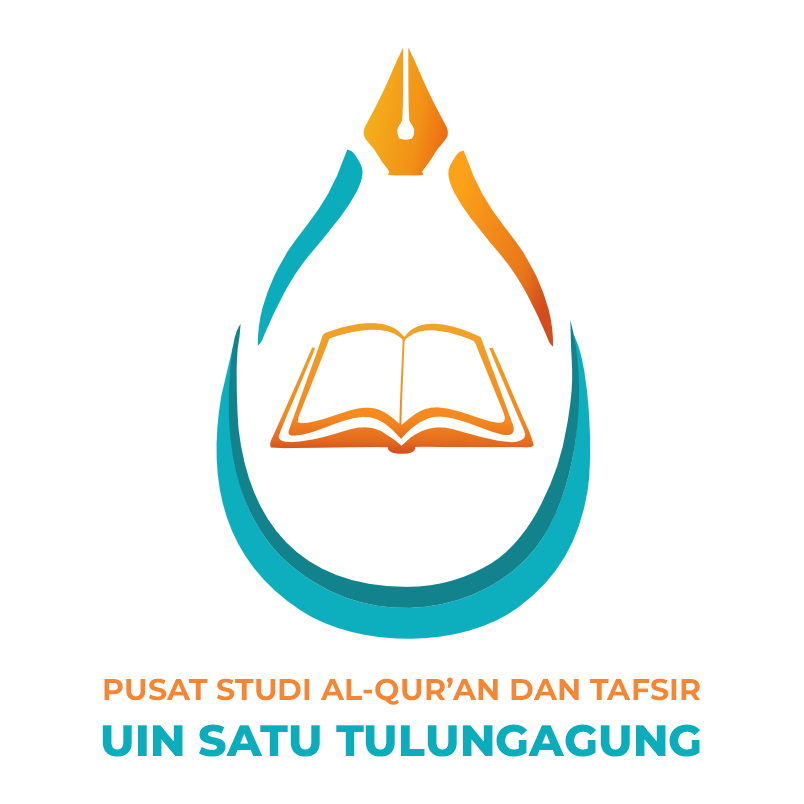
Tinggalkan Balasan